Oleh: Sri Radjasa M.BA
“Negara bisa runtuh bukan karena perang, tapi karena kehilangan kepercayaan.” Kalimat itu diucapkan seorang ilmuwan politik, Samuel Huntington, lebih dari setengah abad lalu.
Namun hari ini, kata-kata itu terasa seperti peringatan bagi Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo turun dari tampuk kekuasaan, negeri ini seolah tidak benar-benar melepaskan bayangannya.
Jokowi memang tidak lagi di istana, tapi pengaruhnya seperti masih menetap di sana. Putranya kini menjadi wakil presiden. Loyalisnya tersebar di kabinet dan lembaga hukum.
Para relawan dan ormas yang dulu menjadi tulang punggung kemenangan politiknya kini menjelma menjadi kekuatan sosial yang masih setia berdiri tegak di bawah “bendera Solo”.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam politik Indonesia, kekuasaan tidak selalu berakhir dengan masa jabatan. Ia bisa berubah wujud menjadi pengaruh, menjadi jaringan, menjadi kekuatan informal yang terus hidup di balik tirai.
Politik Bayangan dan Luka Kepercayaan
Kehidupan politik Indonesia pasca 2024 tampak seperti panggung yang sama dengan pemain baru, tapi dengan sutradara lama. Ketika pemerintahan Prabowo-Gibran mulai bekerja, publik belum sepenuhnya percaya bahwa ini babak baru.
Banyak kebijakan justru terasa seperti kelanjutan masa lalu dimana penempatan pejabat yang itu-itu juga, proyek besar yang dikerjakan dengan cara lama, dan bahasa politik yang penuh eufemisme tapi miskin arah.
Sebagian orang menyebut munculnya “operasi garis dalam” berupa gerakan halus yang bekerja dari balik layar, untuk menjaga agar kekuasaan lama tetap punya napas dalam pemerintahan baru.
Apakah itu benar? Tak ada bukti terang. Namun tanda-tandanya terasa.
Ketika kebijakan yang diambil pemerintah tampak tidak populer, seperti soal tanggung jawab proyek kereta cepat Whoosh, atau pembentukan tim reformasi Polri yang justru diisi nama-nama lama yang muncul pertanyaan di ruang publik, siapa sebenarnya yang mengendalikan arah negara ini?
Narasi di media sosial pun berkembang cepat. Istilah “Presiden omon-omon” menjadi peluru propaganda yang tajam. Ia menyebar melalui jaringan buzzer yang terorganisir, menggunakan luka batin rakyat sebagai bahan bakarnya.
Kekecewaan terhadap janji perubahan, frustrasi atas ketimpangan ekonomi, dan kejenuhan terhadap korupsi menjadi energi yang mudah diledakkan. Itulah politik zaman ini, dimana perang tidak lagi memakai senjata, tapi memakai persepsi.
Negara di Persimpangan
Bagi bangsa yang pernah hancur karena konflik internal, seperti Yugoslavia di tahun 1990-an, kehancuran tidak datang dari luar, tapi dari dalam mulai dari syahwat kekuasaan elite yang tak pernah cukup, dan dari rakyat yang kehilangan kepercayaan.
Indonesia tidak kebal terhadap risiko itu.
Presiden Prabowo kini berada di tengah pusaran. Ia harus menavigasi pemerintahan yang sebagian besar dibentuk dari kompromi, bukan visi. Ia harus mengendalikan kabinet yang diisi oleh orang-orang dengan kesetiaan ganda, dimana sebagian kepada negara, sebagian kepada masa lalu.
Dan di atas semuanya, ia harus merebut kembali satu hal yang paling mahal dalam politik yakni kepercayaan rakyat.
Kalau Prabowo gagal membaca situasi, ia akan menjadi presiden yang tampak berkuasa tetapi sebenarnya terpenjara dalam sistem yang dikendalikan dari luar.
Kekuasaan memang bisa diwariskan, tapi kewibawaan tidak.
Kewibawaan hanya lahir dari keberanian untuk berdiri di atas semua kepentingan, termasuk kepentingan orang yang dulu menolong kita naik.
Menjadi Pemimpin, Bukan Bayangan
Sejarah mencatat, banyak pemimpin besar justru diuji bukan oleh musuh, tapi oleh bayang-bayang kekuasaan sendiri.
Soekarno tumbang bukan karena lawan luar, tetapi karena perpecahan di dalam kekuasaannya.
Soeharto jatuh bukan karena serangan asing, tapi karena rakyat kehilangan kepercayaan.
Jokowi sendiri, yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perubahan, akhirnya juga terjebak dalam jebakan kekuasaan yang ia bangun sendiri, dimana terlalu banyak loyalis, terlalu sedikit koreksi.
Kini ujian itu berpindah ke tangan Prabowo. Ia harus membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak akan menjadi sekadar “lanjutan dari Jokowi”, melainkan koreksi terhadap cara bernegara yang sudah terlalu lama memanjakan kekuasaan pribadi di atas kepentingan publik.
Jika Prabowo hanya sibuk mengurus citra, tanpa memutus jaringan kekuasaan lama yang masih hidup di sekitar istana, maka ia akan gagal mengembalikan marwah kepemimpinan nasional.
Dan jika itu terjadi, rakyat akan kembali menjadi penonton di negeri sendiri, dengan menatap panggung yang sama, dengan aktor berbeda tapi naskah yang tak pernah berubah.
Menyelamatkan Negeri dari Diri Sendiri
Huntington menulis bahwa negara yang gagal memperkuat institusi akan berjalan menuju chaos yang terorganisir. Maka tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menghindari kudeta atau krisis ekonomi, tetapi menyelamatkan negara dari dirinya sendiri, dari jebakan dinasti, patronase, dan politik balas jasa.
Kekuatan informal seperti “genk Solo” yang disebut sebagian pengamat, tidak akan punya ruang jika lembaga negara benar-benar kuat dan independen.
Namun selama penegakan hukum masih tunduk pada kepentingan politik, selama aparat keamanan belum bebas dari intrik internal, dan selama elite politik lebih memilih kompromi daripada keberanian moral, maka bayangan itu akan terus hidup di istana, siap mengatur arah pemerintahan dari balik layar.
Indonesia butuh pemimpin yang bukan hanya berani berperang, tetapi juga berani menahan diri.
Pemimpin yang tidak takut kehilangan teman ketika membela kebenaran.
Pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan bukan alat membalas budi, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan.
Prabowo punya peluang untuk menulis sejarah baru, tapi hanya jika ia memilih menjadi negarawan, bukan pelanjut bayangan.
Karena di atas segalanya, sejarah tidak mengingat siapa yang berkuasa paling lama, melainkan siapa yang berani berdiri paling tegak ketika kebenaran diuji.
Bangsa ini telah melewati banyak badai, dari krisis 1998 hingga pandemi global. Tapi ancaman terbesar justru kini: bila rakyat kehilangan kepercayaan dan institusi kehilangan wibawa.
Jika itu terjadi, Indonesia bisa retak bukan karena serangan asing, tetapi karena erosi dari dalam oleh elite yang tak pernah puas dan rakyat yang mulai letih berharap.
Maka, satu-satunya jalan adalah kembali pada akal sehat kenegaraan yaitu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, memutus mata rantai loyalitas gelap, dan menegakkan moral politik di atas kekuasaan.
Karena republik ini tidak akan jatuh oleh lawan, melainkan oleh pengkhianatan dalam diam.
Penulis adalah: Pemerhati Intelijen

















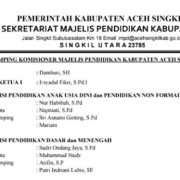














Comments